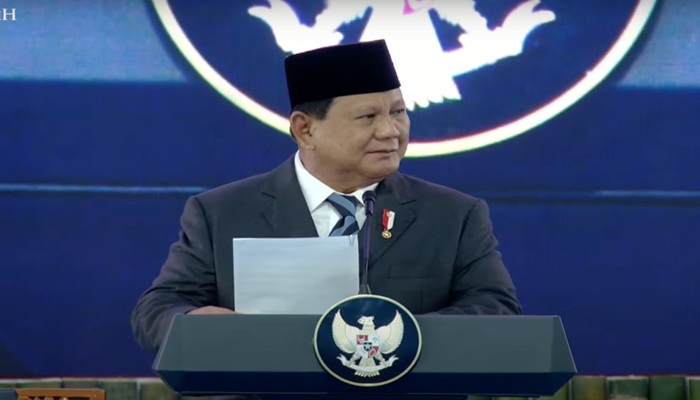APAAJA.NET – Keraton Yogyakarta bukan sekadar bangunan tua bersejarah. Ia adalah simbol peradaban Jawa, pusat kekuasaan, dan penjaga warisan budaya yang masih hidup hingga hari ini. Salah satu momen penting dalam catatan sejarahnya adalah pertemuan Sultan Hamengkubuwono VIII dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Bijleveld, pada tahun 1937 — peristiwa yang tidak hanya sarat makna politik, tetapi juga diplomasi strategis antara penguasa lokal dan penjajah kolonial.
Pertemuan Elit: Simbol Pengakuan Kekuasaan Keraton oleh Kolonial
Kedatangan Bijleveld ke Keraton Yogyakarta bukan kunjungan biasa. Itu adalah bentuk pengakuan resmi dari pemerintah kolonial atas eksistensi dan pengaruh Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pertemuan ini menegaskan bahwa meski di bawah bayang-bayang penjajahan, keraton tetap memiliki otoritas politik dan simbolis yang diakui oleh pihak kolonial.
Baca Juga: Lebih Mulia dari Surga? Ini Keutamaan Bertetangga dengan Para Nabi di Akhirat!
Asal Mula Keraton: Dari Pesanggrahan ke Pusat Kerajaan Mataram Baru
Keraton Yogyakarta dibangun tak lama setelah ditandatanganinya Perjanjian Giyanti tahun 1755, yang memecah Kerajaan Mataram menjadi dua: Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Sultan Hamengkubuwono I kemudian membangun keraton di lokasi strategis, yang dipercaya dulunya adalah Pesanggrahan Garjitawati—tempat peristirahatan jenazah raja-raja Mataram sebelum dimakamkan di Imogiri.
Makna Sengkala Dwi Naga Rasa Tunggal
Pindahnya pusat pemerintahan ke keraton baru ditandai oleh candra sengkala “Dwi Naga Rasa Tunggal” (1756 M), simbol filosofi tentang kesatuan spiritual, kewibawaan, dan harapan kemakmuran bagi kerajaan yang baru lahir.
Tujuh Kompleks Sakral dan Arsitektur Filosofis Keraton
Keraton Yogyakarta terdiri dari tujuh pelataran inti:
- Siti Hinggil Lor
- Kamandhungan Lor
- Sri Manganti
- Kedhaton
- Kamagangan
- Kamandhungan Kidul
- Siti Hinggil Kidul
Setiap bagian memiliki fungsi dan makna filosofis tersendiri, mulai dari spiritualitas, politik, hingga pendidikan adat. Tata ruangnya menggambarkan kosmologi Jawa, di mana keraton adalah pusat semesta.
Keraton sebagai Lembaga Adat dan Pusat Budaya Hidup
Keraton tidak hanya berfungsi sebagai kediaman Sultan. Ia adalah lembaga adat aktif yang mengelola upacara sakral, menyimpan pusaka keraton, dan melestarikan kesenian Jawa seperti gamelan, tari klasik, batik, dan kerajinan.
Calon Warisan Dunia UNESCO
Pada tahun 1995, Keraton Yogyakarta dicalonkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO, pengakuan atas pentingnya nilai sejarah dan budaya yang dimiliki keraton, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia.
Jejak Diplomasi yang Menguatkan Peran Keraton
Pertemuan antara Sultan Hamengkubuwono VIII dan Gubernur Jenderal Bijleveld menunjukkan bahwa Keraton Yogyakarta bukan hanya simbol budaya, tapi juga aktor politik penting di era kolonial. Kini, keraton tetap menjadi penjaga nilai-nilai adiluhung dan penghubung antara masa lalu dan masa depan bangsa.***